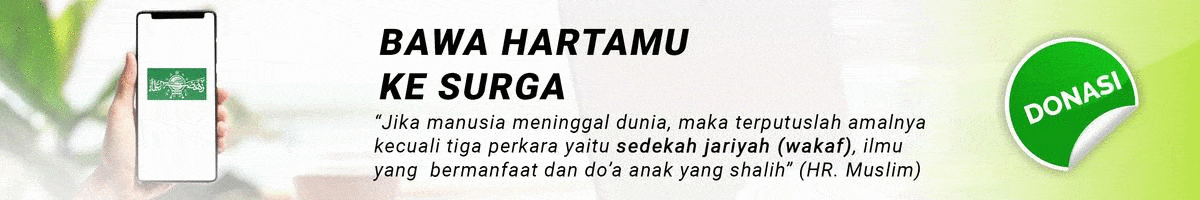Latar belakang historis kelahiran Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi memiliki sejumlah interpretasi. Setidaknya ada tiga interpretasi yang seringkali digunakan untuk menjelaskan sejarah kelahiran NU.
Pertama, penjajahan oleh bangsa Eropa yang juga diikuti penyebaran agama Kristen mendorong para ulama untuk melakukan respon, di antaranya perlawanan kultural lewat jalur pendidikan dan dakwah. Para ulama sadar bahwa sikap non kooperatif terhadap politik etis Belanda tidak mungkin dilakukan bila tanpa memperkuat kembali jaringan ulama dan pesantren, dan ini ditafsirkan sebagai embrio lahirnya NU.
Kedua, kebangkitan umat Islam, selain membawa dampak positif ternyata juga membaga ekses negatif, yaitu munculnya masalah khilafiyyah furu’iyyah. Berbagai serangan kaum pembaharu yang meremehkan ulama penganut madzhab dalam praktek beragama, mendorong ulama untuk merespon dalam bentuk pembelaan terhadap faham Ahlussunnah wal jama’ah dan sistem madzhab. Upaya merespon serangan kaum pembaharu ini juga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya NU.
Ketiga, jatuhnya Khilafah Usmaniyah Turki, dan disusul dengan jatuhnya Hijaz ke dalam kekuasaan kaum Wahabiyyah, ini dikhawatirkan oleh para ulama dapat berakibat dilarangnya kehidupan bermadzhab di Haramain, dan karena itu para ulama berusaha untuk memperjuangkan agar kehidupan bermadzhab tidak dilarang. Perebutan dalam penentuan anggota komite dalam Konggres Dunia Islam juga tampil sebagai faktor penentu yang melatarbelakangi lahirnya NU.
Penjajahan di belahan dunia Islam dan penyebaran agama Kristen merupakan usaha simbiotik yang tidak dapat dipisahkan. H. Kraemer menyatakan bahwa perluasan kolonial dan ekspansi agama Kristen merupakan gejala simbiose yang saling menunjang. Arogansi Barat yang menganggap bangsa-bangsa lain dan agama mereka sebagai primitif dan “uncivilized”, dikejutkan oleh kekalahan demi kekalahan dalam perang Salib yang berkepanjangan selama kurang lebih 175 tahun (1095 – 1270). Belum lagi sembuh dari luka perang Salib, Yerusallem dengan Bait al-Maqdisnya yang dianggap tempat suci orang Kristen, pada tahun 1453 jatuh ke tangan Islam. Eropa dikejutkan jatuhnya Bizantium –Imperium Kristen di Timur– ke dalam kekuasaan Islam di bawah pimpinan Muhammad al-Fatih, Khalifah Turki Usmani. Bahkan Turki berhasil menguasai Bulgaria, Yugoslavia, Rumania, Hungaria dan berkembang terus ke Barat sampai batas Benteng Wina.
Berbagai kekalahan ini dipandang Eropa bukan hanya sebagai kekalahan politik, namun juga kekalahan agama. Oleh karena itu, hal ini menimbulkan kebencian terhadap Islam dan dunia Islam, sehingga memupuk dendam untuk membalas dan menguasai Islam pada suatu ketika kelak. Atas restu Paus Alexander VI, Spanyol dan Portugal yang dipersatukan lewat perkawinan politik antara Raja Ferdinand II dengan Issabella, berhasil menghancurkan Islam di Spanyol (1492). Berdasarkan Perjanjian Tordesillas (7 Juni 1494), Spanyol dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah di belahan Barat Spanyol menjadi bagian Spanyol dan belahan Timur Spanyol menjadi bagian Portugis.
Peristiwa historis ini dapat ditafsirkan bahwa Paus Alexander VI sebagai pucuk pimpinan agama Kristen pada waktu itu telah merestui dan memberi mandat kepada Spanyol dan Portugis untuk menghancurkan dan menjajah bangsa-bangsa Islam. Sejak itu timbul semangat reconquistia (penaklukan), dengan memberangkatkan para conquistador dan angkatan crusade (angkatan perang Salib), dari Barat ke dunia Timur, terutama dunia Islam, yang bertujuan untuk merebut kembali wilayah mereka dan memperluas pengaruh agama Kristen.
Demikian pula dengan bangsa Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda yang berdatangan silih berganti ke wilayah Nusantara, selalu dibalut oleh tiga semangat sekaligus : ekonomi (gold), politik (glory) dan agama (gospel). Bangsa Belanda yang menginjakkan kakinya pertama kali di Indonesia pada akhir abad XVI, dalam perkembangannya, yaitu pada tahun 1602 memperkuat kedudukannya dengan memonopoli perdagangan melalui VOC (Vereenidge Oast Indische Compagnie). Kekuasaan Belanda di Nusantara ini mengalami pasang surut, ditandai dengan bubarnya VOC pada tahun 1799 dan jatuhnya Kerajaan Belanda ke tangan Perancis pada tahun 1806, ini diikuti jatuhnya Indonesia ke tangan Inggris (sekutu Perancis) pada tahun 1811. Belanda berkuasa kembali di Indonesia, menyusul dikalahkannya Perancis oleh Kerajaan Belanda pada tahun 1814, dan sejak itu penjajahan Belanda semakin kuat.
Sebenarnya perlawanan rakyat Indonesia yang dipimpin para ulama tak pernah reda dari masa ke masa. Sejarah mencatat perlawanan Iskandar Muda di Aceh tahun 1511, Sultan Demak (1512, 1526 dan 1527), Sultan Babullah Ternate 1575, Sultan Agung Mataram 1628-1629, Sultan Hasanuddin di Goa, Pangeran Diponegoro 1825-1830, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Teungku Umar dan Tjut Nyak Din di Aceh. Berbagai perlawanan itu seringkali mudah dipatahkan, selain karena kalah dari segi persenjataan, politik devide et impera juga digunakan dalam menghadapi berbagai perlawanan itu.
Seorang pendeta bernama Simon menyatakan bahwa persatuan umat Islam harus dipecah, sehingga missi sanggup menasranikan kaum muslimin, karena bila kaum muslimin bersatu akan menjadi bahaya dan kutukan bagi dunia missionaris. Pernyataan ini menunjukkan bahwa “politik pecah belah” memiliki dua dimensi kepentingan, yaitu kepentingan penaklukan politik dan agama sekaligus.
Dalam hal ini Snouck Hurgronje –seorang advisser pemerintah kolonial Belanda– secara tegas menyatakan bahwa berkembangnya pengaruh Belanda di Timur tidaklah semata-mata bermaksud mencari keuntungan material, namun juga lebih banyak dimaksudkan untuk mengembangkan agama Kristen. Gubernur Jenderal A.W.F. Idenburg yang berkuasa di Hindia Belanda 1909-1916 sebagai penggagas Kristening Politiek menyatakan bahwa Kristening Politiek tidak saja akan memperkuat agama Kristen di negeri jajahan, namun juga agar kekuasaan penjajah lebih kokoh dan sulit dilepaskan. Lebih lanjut Idenburg menyatakan bahwa dapat tetap dipertahankannya tanah jajahan Indonesia tergantung kepada dapat dikristenkannya atau tidak rakyat Indonesia, bahkan ia bertekad agar penjajah Belanda tetap menguasai Indonesia sampai agama Kristen menjadi agama bangsa Indonesia.
Dalam rangka memperkuat Kristening Politiek, Snouck Hurgronje melancarkan Islam Politiek, yaitu politik “netralitas agama” yang mengakui dan memberikan kebebasan beragama sepanjang tidak mengganggu ketertiban dan keamanan. Politik keagamaan ini bersifat “dualistis”, yaitu memisahkan antara Islam sebagai doktrin agama dan Islam sebagai doktrin politik, atau splitsing-theory sebagaimana disebutkan oleh Kernkomp. Snouck Hurgronje membagi masalah Islam atas tiga kategori : 1) bidang agama murni, 2) bidang sosial kemasyarakatan, dan 3) bidang politik. Dalam bidang agama murni dan sosial kemasyarakatan, Belanda memberi kebebasan sepanjang tidak mengganggu ketertiban dan keamanan. Sementara di bidang politik, segala politik keislaman akan dicegah secara represif, bahkan kalau perlu akan dihadapi dengan kekerasan. Politik keagamaan dualistis ini, oleh H.J. Benda disebut sebagai “politik kembar” antara toleransi dan kewaspadaan, karena memang motivasi dan orientasinya adalah untuk kelestarian kekuasaan pemerintah kolonial.
Dalam rangka status quo ini, Belanda juga melancarkan politik asosianisme atau asimilasionisme, yang dikenal juga sebagai Etische Politiek, yaitu suatu politik yang berupaya membalas budi rakyat jajahan, di antaranya melalui pendidikan. Pendidikan dengan sistem Barat yang ditawarkan penjajah ini, di antaranya adalah untuk memperkuat loyalitas terhadap pemerintah Belanda, memoderasikan sikap keagamaan Islam, dan menyiapkan tenaga-tenaga birokrasi pemerintahan Belanda dari kaum pribumi.
Kaum ulama tradisional lebih berhati-hati dan “non kooperatif” dalam menanggapi politik etis ini, bahkan ada kecenderungan untuk melakukan perlawanan secara kultural. Dalam berbagai dakwahnya, para ulama melarang untuk meniru-niru (tasyabbuh) kebiasaan orang kafir, yang dalam hal ini ditujukan kepada kaum penjajah Belanda.
Bentuk-bentuk perlawanan kultural kaum ulama ini ditunjukkan dengan mengintensifkan lembaga-lembaga pendidikan mereka, yaitu pesantren dan madrasah. Pendidikan di pesantren ini digunakan kaum ulama untuk membentengi pengaruh yang disebarkan kaum penjajah, dan sekaligus untuk menyiapkan kader-kader ulama. Para kyai pesantren mengajarkan berbagai materi pengajiannya dengan muatan-muatan yang membangkitkan semangat nasionalisme.
Sementara penjajahan Belanda dan Kristening Politiek masih berjalan, di dalam umat Islam Indonesia dihadapkan kepada pertentangan yang semakin tajam, yang disebabkan masalah madzhab dan khilafiyah furu’iyyah. Kebangkitan dunia Islam di penghujung abad XIX dan awal abad XX, ternyata diiikuti dengan berbagai perdebatan tajam seputar masalah madzhab dan khilafiyah furu’iyyah. Perdebatan ini semakin memperluas dan memperdalam jurang perbedaan antara golongan-golongan dalam Islam, khususnya antara yang memegangi madzhab dan yang anti madzhab. Kedua golongan ini saling memperkokoh argumentasi dan barisannya. Kelompok anti madzhab semakin meningkatkan serangan-serangannya, sementara kelompok bermadzhab yang dipelopori para kyai dan ulama pesantren terus berusaha menggalang kekuatan untuk menghadapi serangan-serangan dari kalangan anti madzhab.
Walaupun diadakan usaha mempersatukan umat Islam oleh Bratanata –seorang tokoh Syarikat Islam (SI) dari Cirebon– dengan membentuk Badan Koordinasi Konggres Islam sebagai wadah koordinasi dan pemersatu yang menampung semua organisasi dan badan-badan Islam, namun belum membawa hasil. Bahkan dalam Konggres Islam pertama di Cirebon tanggal 31 Oktober – 2 Nopember 1922 yang dipimpin oleh H.O.S. Tjokroaminoto dan Agus Salim, perdebatan antar kelompok semakin sengit. Muhammadiyah dan Al-Irsyad yang diwakili Ahmad Syurkati menuduh madzhab sebagai sumber penyebab kebekuan dan kemunduran umat Islam. Sementara kalangan ulama madzhab yang diwakili oleh K.H. Abdul Wahab dan K.H.R. Asnawi sebaliknya menuduh orang-orang yang menentang madzhab justru akan membuat madzhab sendiri dengan menafsirkan Al-Qur’an dan Hadits sesuka hatinya.
Konggres Islam yang diadakan selanjutnya juga kurang membawa hasil, sehingga perseteruan yang diwarnai oleh perdebatan khilafiyah semakin meningkat. Alfian mencatat bahwa ada gejala yang kuat, kaum anti madzhab –yang sering disebut sebagai kaum pembaharu– semakin menunjukkan kecongkakan dan sikap arogansinya terhadap kaum penganut madzhab, yang pada gilirannya membawa perpecahan di antara keduanya semakin sulit dipersatukan kembali.
Sementara itu dunia Islam dikejutkan oleh berita jatuhnya Khilafah Usmaniyah ke tangan sekularis Musthafa Kamal, dan dihapusnya sistem khilafah berubah menjadi berbentuk Republik Turki. Pada saat yang hampir bersamaan, Hijaz (di dalamnya termasuk Makkah dan Madinah) jatuh ke tangan kekuasaan kalangan Wahabiyah, sehingga menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi ulama penganut madzhab di Indonesia bahwa kelak penguasa akan melarang praktek kehidupan beragama ala Ahlussunnah wal Jama’ah yang menganut madzhab.
Krisis kekhilafahan ini dimanfaatkan oleh Raja Hijaz Syarief Husein bin Ali untuk mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah Islam yang baru. Tindakan terburu-buru dan cukup gegabah Raja Husein ini dinilai akan mengancam wibawa kerajaan Najed, dan ini mendorong Raja Abdul Aziz bin Saud menggerakkan tentaranya untuk menyerang Hijaz. Pada tanggal 13 Oktober 1924, Makkah sebagai pusat kekuasaan Husein jatuh ke Tangan Raja Ibnu Saud, dan pada 5 Desember 1924 Madinah berhasil dikuasai, selanjutnya Syarief Husein atas bantuan Inggris melarikan diri ke Ciprus. Setelah berhasil menguasai seluruh Hijaz, Abdul Aziz Bin Saud pada 8 Januari 1926 memproklamasikan diri sebagai Raja Arab baru yang berkedudukan di Makkah.
Para ulama Mesir yang dipelopori oleh ulama Al-Azhar berusaha mengadakan Muktamar Dunia Islam untuk membicarakan soal khilafah ini. Maka diundanglah para pemimpin Islam dari berbagai negara-negara Islam, termasuk Indonesia, untuk menghadiri muktamar yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Maret 1925.
Begitu undangan dari Mesir diterima di Indonesia, pada tanggal 24-26 Desember 1924 diadakan Konggres Al-Islam di Surabaya, yang hasilnya di antaranya adalah dibentuknya Central Comite Chilafat beranggotakan berbagai organisasi Islam dan diketuai oleh Wondo Soedirdjo (Wondoamiseno) dari SI. Konggres mengusulkan agar khilafah tetap dipertahankan dan dipegang secara kolektif oleh sebuah “Majlis Ulama” yang diwakili oleh ulama-ulama terkemuka dunia, dan hendaknya berkedudukan di Makkah. Konggres juga memutuskan akan mengirim delegasi yang terdiri dari Suryo Pranoto (SI), KH. Fachruddin (Muhammadiyah), dan KH. Abdul Wahab Chasbullah (mewakili ulama Surabaya).
Namun karena kurang mendapat dukungan dari dunia Islam secara luas, dan situasi dalam negeri masing-masing negara Islam kurang menguntungkan, maka muktamar yang direncanakan di Kairo itu gagal. Akibatnya utusan Indonesia pun tidak jadi berangkat.
Kekhawatiran ulama penganut madzhab terhadap kekuasaan Ibnu Saud di Hijaz akan menyebarkan paham Wahabiyah menjadi kenyataan, menyusul tersiarnya kabar bahwa telah terjadi pembunuhan ulama-ulama yang tidak sepaham, dan penghancuran tempat-tempat yang dianggap suci. Demikian pula terjadi perombakan dalam praktek-praktek keagamaan yang selama ini dianggap mapan, seperti larangan bermadzhab, larangan berziarah ke tempat-tempat yang dianggap keramat, dan berbagai larangan itu diikuti dengan ancaman hukuman mati bagi yang melanggarnya.
Kondisi ini mendorong ulama madzhab dan penganut ahlussunnah wal jamaa’ah di Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam mempertahankan praktek-praktek keagamaan ala ahlussunnah wal jama’ah di tanah Hijaz. Pada saat diselenggarakan Konggres Islam IV di Yogyakarta pada 21-27 Agustus 1925, bersamaan dengan Konggres Syarikat Islam, kaum ulama madzhab yang dipelopori KH. Abdul Wahab mengusulkan agar dalam Muktamar tentang khilafah yang akan diadakan oleh Ibu Saud pada Juni 1926 di Makkah nanti, delegasi Indonesia mendesak Raja Ibnu Saud untuk melindungi dan mempertahankan kebebasan bermadzhab. Abdul Wahab tidak setuju kalau delegasi Indonesia hanya sekedar menyatakan perasaan solidaritas atas jatuhnya khilafah Islam saja, namun juga harus dipersoalkan tentang jatuhnya Hijaz ke tangan kekuasaan Ibnu Saud. Kaum pembaharu dengan dipelopori Syarikat Islam, Muhammadiyah dan Al-Irsyad yang sejak semula arogan dan mendominasi Konggres Islam, menurut Alfian, menolak usul Abdul Wahab dan menilai usul itu tidak pada tempatnya.
Setelah undangan resmi Raja Ibnu Saud untuk menghadiri Muktamar Dunia Islam sampai di Indonesia, maka pada tanggal 6 Pebruari 1926 diadakan Konggres Islam V di Bandung untuk merumuskan bahan dan utusan yang akan dikirim ke muktamar tersebut. Secara kebetulan KH. Abdul Wahab –wakil ulama madzhab yang selalu mengikuti perkembangan Konggres Islam– mendadak pulang ke Jombang dan tidak dapat meneruskan ikut konggres, karena ayahnya –KH Chasbullah– wafat. Hal ini diambil kesempatan oleh kaum pembaharu untuk semakin mendominasi Konggres, dan usul ulama madzhab dalam Konggres Islam V di Bandung ini semakin tidak mendapat perhatian, serta ulama madzhab tidak diikutsertakan dalam delegasi Muktamar di Makkah. Delegasi muktamar terdiri dari HOS. Tjokroaminoto (Syarikat Islam), KH. Mas Mansur dan H. Soedjak (keduanya dari Muhammadiyah), dan ditambah H. Abdullah Ahmad dan H.A. Karim Amrullah, keduanya mewakili kaum pembaharu di Sumatera Barat. Delegasi berangkat ke Makkah pada tanggal 2 Maret 1926 dengan menggunakan kapal Rondo melalui pelabuhan Surabaya.
Kalangan ulama madzhab yang merasa diabaikan, atas gagasan KH. Abdul Wahab dengan restu KH. Hasyim Asy’ari, membentuk komite sendiri untuk mengirim delegasi ke muktamar di Makkah. Komite yang kemudian diberi nama Komite Hijaz ini diketuai oleh H. Hasan Gipo, H. Saleh Syamil sebagai sekretaris, dan KH. Abdul Halim dan KH. Kholil Masyhuri sebagai pembantu, sementara KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Abdul Wahab sebagai penasehat. Komite mengawali kegiatannya dengan mengundang ulama-ulama terkemuka dan mempersiapkan pertemuan.
Pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriyah, bertepatan dengan 31 Januari 1926, pertemuan ulama digelar di Kertopaten Surabaya, di rumah Kyai Musa –mertua KH. Abdul Wahab. Para ulama yang hadir dalam pertemuan itu di antaranya adalah KH. Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang, KH. Abdul Wahab Tambakberas Jombang, KH. Bisri Syansuri Denanyar Jombang, KH. Doro Muntoha (menantu KH. Kholil) Bangkalan Madura, KH. R. Asnawi Kudus, KH. Nawawi Pasuruan, KH. Ridlwan Mujahid Semarang, KH. Abdul Hamid Faqih Sedayu Gresik, KH. Zubair Gresik, KH. Abdul Halim Liewemunding Cirebon, KH. Maksum Lasem Rembang, KH. Nachrowi Malang, KH. Dahlan Abdul Qohar Kertosono, KH. Ridlwan Abdullah, KH. Mas Alwi Abdul Aziz dan KH. Abdullah Ubaid, ketiganya dari Surabaya, Syekh Ahmad Ghonaim al-Misri dari Mesir, dan beberapa ulama lainnya.
Pertemuan para ulama yang dipimpin oleh KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Abdul Wahab Chasbullah ini membicarakan masalah pengiriman delegasi ke Makkah dan masalah penting lainnya, yaitu : 1) tentang kristenisasi dan sikap acuh tak acuh terhadap agama yang ditunjukkan oleh beberapa orang tertentu; 2) perjuangan umat Islam dalam menentukan nasib rakyat dan tanah air; 3) menghadapi aliran baru yang anti madzhab; 4) persatuan ulama ahlussunnah wal jama’ah untuk meningkatkan perjuangan; dan 5) menghadapi ancaman kaum wahabiyah terhadap paham ahlussunnah wal jama’ah di tanah Hijaz.
Pada pertemuan itu diresmikan Komite Hijaz yang telah dibentuk sebelumnya, dan memutuskan mengirim KH. R. Asnawi dari Kudus sebagai utusan ulama Indonesia untuk menghadap dan mengajukan permohonan kepada Raja Ibnu Saud, yaitu : 1) meminta kepada Raja Ibnu Saud untuk tetap memberlakukan kebebasan bermadzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali); 2) memohon tetap diramaikannya tempat-tempat bersejarah, karena tempat tersebut telah diwakafkan untuk masjid, seperti tempat kelahiran Siti Fatimah, bangunan Khoizuron dan lain-lain; 3) mohon agar disebarluaskan waktunya musim haji, mengenai hal ihwal haji, baik ongkos haji, perjalanan keliling Makkah maupun tentang Syekh; 4) mohon hendaknya semua hukum yang berlaku di Hijaz ditulis sebagai undang-undang, supaya tidak terjadi pelanggaran hanya karena belum ditulisnya undang-undang tersebut; dan 5) jam’iyah ulama mohon jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa utusan sudah menghadap Raja Ibnu Saud dan sudah menyampaikan usul-usul tersebut.
Dalam musyawarah ulama itu muncul persoalan, atas nama siapa pengiriman delegasi ke Makkah tersebut. Jawaban spontan dari para ulama adalah kesepakatan untuk membentuk suatu jam’iyah (organisasi) sebagai wadah bagi persatuan dan perjuangan para ulama. Berkenaan dengan nama jam’iyah itu muncul dua usul. Pertama, KH. Abdul Hamid Faqih dari Sedayu Gresik mengusulkan agar jam’iyah tersebut diberi nama Nuhud al-Ulama yang berarti kebangkitan ulama, dengan harapan para ulama bersiap-siap akan bangkit melalui jam’iyah tersebut. Kedua, KH. Mas Alwi Abdul Aziz dari Surabaya mengusulkan agar jam’iyah itu diberi nama Nahdhah al-Ulama, yang artinya kebangkitan ulama secara bersama-sama yang terorganisir, iqtibas kepada Nahdhah al-Wathan, yang menunjukkan adanya kebangkitan ulama yang sudah dirintis sejak lama. Akhirnya secara aklamasi usul KH. Mas Alwi Abdul Aziz diterima oleh forum musyawarah karena dianggap lebih cocok. Pada hari itu juga, yaitu tanggal 16 Rajab 1344 Hijriyah atau 31 Januari 1926 Miladiyah, jam’iyah Nahdlatul Ulama dinyatakan resmi berdiri.
KH. R. Asnawi yang dalam musyawarah diputuskan menjadi utusan menghadap Raja Ibnu Saud gagal berangkat, karena ketinggalan kapal. Agar misi ulama tidak gagal, maka keputusan musyawarah ulama di Surabaya dikirim melalui telegram langsung kepada Raja Ibnu Saud. Setelah mengirim telegram dua kali yang menghabiskan biaya masing-masing senilai f. 113.83 dan f. 261.20, dan ditunggu selama dua tahun, jawaban belum juga datang. Karena hal itu, maka KH. Abdul Wahab bersama Syekh Ahmad Gonaim al-Misri berangkat menghadap Raja Ibnu Saud di Makkah, dan menyampaikan apa yang menjadi keinginan para ulama Indonesia. Utusan dan surat NU itu mendapat sambutan yang menggembirakan dari Raja Ibnu Saud, dan ia meluluskan permintaan NU sebagaimana dinyatakan dalam surat jawabannya kepada Pengurus Besar NU No. 2082 tertanggal 13 Juni 1928.
Pada hari kelahiran NU itu berhasil pula disusun pengurus lengkap, yang terdiri dari Syuriyah (Dewan Ulama atau legislatif), Mustasyar (Dewan Pertimbangan) dan Tanfidziyah (Badan Pelaksana atau Eksekutif). Susunan pengurus NU adalah :
Syuriyah : KH. Muhammad Hasyim Asy’ari Jombang (Rais Akbar), KH. Ahmad Dahlan Achyad Surabaya (Wakil Rais), KH. Abdul Wahab Chasbullah Surabaya (Katib), KH. Abdul Halim (asal Cirebon ) Surabaya (Naibul Katib); A’wan : KH. Mas Alwi Abdul Aziz Surabaya, KH. Ridlwan Abdullah Surabaya, KH. Amin Abdus Syukur Surabaya, KH. Amin Surabaya, KH. Said Surabaya, KH. Nachrowi Thahir Malang, KH. Chasbullah Surabaya, KH. Syarif Surabaya, KH. Yasin Surabaya, KH. Nawawi Amin Surabaya, KH. Bisri Syansuri Jombang, KH. Abdul Hamid Jombang, K. Abdullah Ubaid Surabaya, KH. Dahlan Abdul Kahar Mojokerto, K. Abdul Madjid Surabaya, dan KH. Masyhuri Lasem.
Mustasyar : KH. Mohammad Zubair Gresik, KH. Raden Munthaha Madura, KH. Mas Nawawi Pasuruan, KH. Ridwan Mujahid Semarang, KH. R. Asnawi Kudus, KH. Hambali Kudus, Syekh Ahmad Ghanaim Surabaya (asal Mesir).
Tanfidziyah : H. Hasan Gipo Surabaya (Ketua), H. Saleh Syamil Surabaya (Wakil Ketua), Mohammad Shadiq Surabaya (Sekretaris), H. Nawawi Surabaya (Wakil Sekretaris), H. Mohammad Burhan dan H. Ja’far Surabaya (keduanya Bendahara).
Lahirnya NU juga disertai dengan beberapa hambatan, baik internal maupun eksternal. Secara internal ada beberapa kyai yang tidak setuju dengan didirikannya jam’iyah NU, bahkan dianggap bid’ah, karena zaman Rasulullah tidak ada usaha yang demikian. Kyai Hasyim (salah seorang guru KH. Hasyim Asy’ari) pengasuh Pondok Pesantren Plangitan Babad yang berasal dari Padangan Cepu bahkan mengharamkan berdirinya NU.
Secara eksternal, reaksi berdirinya NU datang dari dua arah, yaitu dari kalangan penjajah dan dari kaum pembaharu. Berdirinya NU hampir bersamaan waktunya dengan sedang berseminya semangat nasionalisme yang menentang penjajah. Oleh karena itu, berhimpunnya para ulama dalam NU juga tidak luput dari kecurigaan pemerintah kolonial Belanda. Dari arah lain, reaksi datang dari kaum pembaharu yang anti madzhab, bahkan mereka secara arogan menuduh NU berdiri atas dukungan Belanda dan disponsori oleh Christiaan van der Plas, seorang ahli Islam dan pegawai tinggi pemerintah kolonial Belanda.
Berdasarkan gambaran di atas, menunjukkan bahwa berbagai peristiwa historis tersebut merupakan latar belakang atau faktor pendorong, baik langsung maupun tidak langsung berdirinya NU. Faktor penjajahan kolonial Eropa yang diikuti dengan politik kristenisasi, menjadi faktor tidak langsung kebangkitan ulama pesantren. Sementara itu dominasi organisasi kaum pembaharu Islam di Indonesia dan serangkaian serangan yang dialamatkan kepada kalangan ulama madzhab, serta kepentingan mempertahankan praktek beragama ala madzhab menyusul berkuasanya Raja Saud di Hijaz yang dinilai membahayakan madzhab, menjadi faktor yang berkaitan langsung dengan berdirinya NU. Dari sini terlihat bahwa berdirinya jam’iyah NU merupakan simbol yang paling jelas atas fenomena kebangkitan ulama pembela tradisi ahlussunnah wal jama’ah di Indonesia.
Sumber:
Musthofa Sonhadji, 2001, “Hubungan Politik Nahdlatul Ulama dan Pemerintah Orde Baru”, Disertasi, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga).